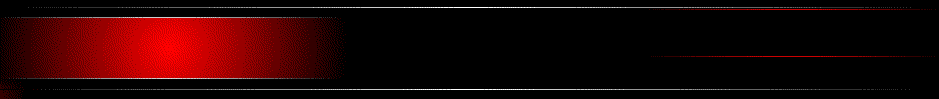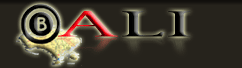|
| Ida Pandita Mpu Jaya Acharya Nanda |
Tapi, saya tidak setuju dengan istilah korban suci itu. Yang lebih tepat adalah aktivitas rela berkorban.
Ketika kita berbicara yadnya dalam aspek upakara, di sana ada konsep dualisme, yakni spirit dan material.
Saat ini banyak umat yang tidak melihat dari konsep spiritnya, tetapi lebih banyak ke unsur material, sehingga hal-hal yang bersifat material lah yang ditonjolkan.
Sarana upakara dijadikan komoditas, dan bahkan dieksploitasi kelompok tertentu.
Terkadang, yadnya dengan bebantenan besar tidak hadir karena keinginan atau kemampuan si pemilik gawe.
Tetapi permintaan oknum tukang banten, dengan tujuan memenuhi target pendapatan.
Akibatnya, sering terjadi, seharusnya bisa memakai satu kerbau, tukang banten meminta lebih dari satu.
Kalau kita berpikir secara rasional, wilayah yadnya itu memang tidak terukur karena merupakan persembahan untuk Tuhan.
Tapi ketika masuk ke dunia material (sarana upakara), kan seharusnya ada ukuran.
Ukuran tersebut harus sesuai dengan desa, kala, patra.
Maksudnya, memperhitungkan jumlah krama dan kemampuan finansial krama.
Dengan konsep ini, sarana upakara di daerah penduduk banyak namun ekonominya menengah ke bawah, tentu akan berbeda dengan daerah yang penduduknya sedikit tapi kaya.
Dalam yadnya, persentase penghasilan dan jumlah krama sangat penting sekali. Karena dalam konsep yadnya, di situ ada kewajiban untuk kita melakukan wairagya atau pelepasan.
Namun di sini terkadang umat kurang menyadari. Apalagi di era sekarang ini, adanya komunikasi lewat media sosial (medsos) yang diramu oleh media-media mainstream menyebabkan masyarakat lebih mudah mempertontonkan egonya.
Sehingga terjadilah desa yang tadinya hanya menggelar upacara kecil, mendadak menggelar upacara besar dengan puluhan kerbau.
Ritual besar itu lantas dipotret dan dipertontonkan di medsos. Itu dilakukan semata-mata untuk reproduksi identitas, supaya desanya disegani.
Kita tidak boleh memungkiri bahwa hal inilah yang sedang terjadi. Kita juga tidak boleh menampik kondisi saat ini bahwa persaingan antar desa di Bali sangat kuat.
Kalau desa A bisa menggelar ritual besar, desa B pasti berupaya supaya bisa melakukan ritual yang lebih besar lagi.
Akibatnya, uang kas desa hanya akan habis untuk yadnya. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, pelaba desa atau pura dijual untuk memenuhi kebutuhan upacara.
Kalau umat berpikir cerdas, uang yang dimiliki desa juga harus digunakan untuk pembangunan sumber daya manusia.
Desa adat harus punya program yang dapat memperbaiki kualitas berpikir dan ekonomi kramanya. Mereka jangan diajak meyadnya saja.
Kalau ini terus terjadi, jangan salahkan kalau di dunia kerja, umat kita hanya menjadi buruh kasar.
Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali harus hadir mencarikan solusi atas keadaan seperti ini. Berikan pencerahan yang rasional kepada umat.
Mohon maaf sekali, selama ini yang terlihat PHDI hanya hadir ketika ada permasalahan, khususnya berkaitan dengan proyek-proyek.
Maka, tidak heran jika ada yang mengatakan PHDI bukan lembaga umat, tetapi hadir sebagai pengganjal proyek A atau melancarkan proyek B. Sebab keseharian umat sangat jarang sekali dibahas PHDI.
sumber : tribun